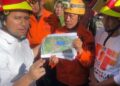Bacaini.id, BLITAR – Jabatan bupati dan wali kota di Pilkada 2024 menjadi rebutan. Setidaknya di Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri, Jawa Timur, dinamika pilkada mulai bergeliat.
Ekspresi politik para kandidat di Pilkada Tulungagung lebih mencolok dibanding Blitar dan Kediri yang berkecenderungan lebih kalem. Terlebih Kabupaten Kediri di mana pilkada calon tunggal diprediksi bakal terulang.
Mereka yang merasa populis, berelektabilitas bagus serta ditunjang modal ekonomi yang kuat, berlomba berebut rekomendasi partai politik pengusung. Utamanya modal dan jaringan, menjadi faktor penentu arah rekom.
Mereka yang bermodal cekak tentunya tidak perlu buang-buang waktu menanti keajaiban politik. Cukup menjadi penonton yang baik.
Begitu juga dengan kandidat bermodal cukup tapi masih mencemaskan duit ludes dan berhemat, lebih baik cepat-cepat mengurungkan niat.
Sebab menjadi bupati maupun wali kota realitasnya dibutuhkan kapital besar. Hal itu setimpal dengan fasilitas saat terpilih nanti, yakni memiliki kekuasaan dan kebijakan penuh atas rakyat.
Lain dulu lain sekarang. Pada masa kolonial Belanda, yakni tepatnya pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), pemerintah Hindia Belanda lebih menyukai patih dan wedana, bawahan bupati.
Sikap politik Belanda terhadap bupati cenderung menghabisi. Pendidikan bupati yang kebanyakan rendah, dibiarkan tetap rendah. Pada tahun 1900, dari sebanyak 72 bupati tercatat hanya 4 bupati yang mengerti bahasa Belanda.
Para bupati sengaja dijebak dalam situasi ketidakmengertian. Mereka dibiarkan melakukan penyelewengan, dan ketika terbukti, kolonial Belanda memiliki alasan untuk merampas wewenang mereka.
“Pada tahun 1900, prestise, kekuasaan dan kepercayaan diri kaum elit bangsawan Jawa mencapai titik rendah,” demikian dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008).
Pada awal pasca Perang Jawa, kolonial Belanda diketahui menjaga jarak dengan keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan memilih mempererat hubungan dengan bupati, patih dan wedana.
Berhubungan dengan bupati, patih dan wedana di Jawa bagi kolonial Belanda lebih menguntungkan. Khususnya dalam penumpasan gerakan Diponegoro terbukti lebih efektif.
Pada tahun 1860 kolonial Belanda mulai mengatur pemerintahan pribumi agar seimbang dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kedudukan Bupati tetap sebagai pejabat pribumi tertinggi.
Namun kekuatan politiknya dikerdilkan agar tidak menjelma sebagai raja-raja kecil di daerah. Yang dilakukan kolonial Belanda adalah menyokong patih dan wedana yang berkedudukan di bawah bupati.
“Lama-kelamaan praktik pihak Belanda melangkahi mereka (bupati) dan lebih menaruh kepercayaan kepada pembantu-pembantu mereka, yaitu para patih”.
Masih dalam rangka menghabisi kekuasaan bupati. Pada tahun 1904 kolonial Belanda menerbitkan Hormat Circulaire (surat edaran tentang etiket) yang intinya secara resmi menghapus penampilan bangsawan Jawa.
Penampilan bupati yang diikuti tanda kebesaran, jumlah pelayan yang banyak serta payung-payung simbol status kebangsawanan, dilucuti. Penampilan itu dinilai ketinggalan jaman.
Kolonial Belanda juga menghapus sebagian besar lambang-lambang feodal kaum elit bangsawan Jawa.
Pada saat bersamaan derajat kewibawaan istana kerajaan telah anjlok, dan hanya sebagai formalitas yang lemah. Istana kerajaan hanya instansi buatan yang rumit dan kuno.
Sementara berlakunya cultuurstelsel atau tanam paksa membuat rakyat berada dalam situasi sosial dan politik yang menderita. Pada saat itu prestise dan kepercayaan diri bangsawan Jawa mencapai titik terendahnya.
Penulis: Solichan Arif