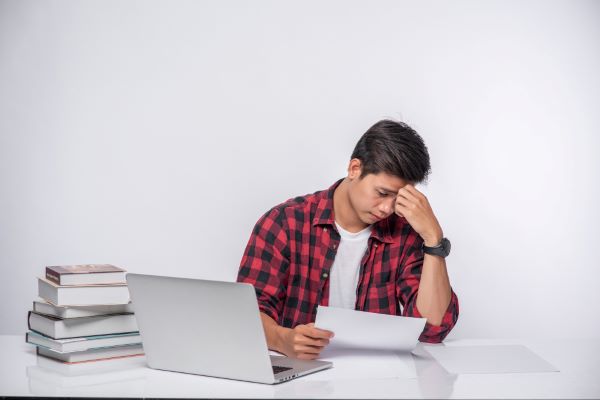Scroll lima menit di TikTok, tiba-tiba kamu “mengidap” anxiety. Lihat satu postingan Instagram, langsung merasa punya trauma. Ini bukan lagi kesadaran kesehatan mental ini self-diagnosis yang berbahaya. Di tengah maraknya kesadaran akan kesehatan mental, muncul fenomena mengkhawatirkan dan berdampak besar yaitu diagnosis diri sendiri tanpa bantuan profesional.
Fenomena ini sering kali ditimbulkan oleh adanya konten media sosial yang menyajikan informasi psikologi secara sederhana. Banyak pengguna yang mengonsumsi konten tersebut merasa relate dengan kata-kata yang yang dideskripsikan dalam konten. Hal tersebut membuat pengguna secara spontan percaya bahwa mereka mengidap kondisi tersebut tanpa pemeriksaan profesional.
Mengapa Self-Diagnosis Bisa Menyesatkan
Self diagnosis didefinisikan sebagai proses individu mencari serta mengidentifikasi suatu gejala dalam diri mereka sendiri dan langsung menyimpulkan kondisi tersebut tanpa konsultasi kepada profesional (Dewi et al., 2022). Hal ini seringkali mereka lakukan dengan mendiagnosis diri mereka sendiri yang mengalami gangguan psikologis hanya berdasarkan pengetahuan atau pemahaman pribadi yang mereka dapatkan melalui sumber-sumber tidak resmi seperti media sosial, teman keluarga, maupun pengalaman pribadi seseorang (Annury et al., 2022).
Secara internasional, berdasarkan laporan dari Sapien Labs (2023), sekitar 27% dari 500.000 partisipan yang berasal dari 71 negara di seluruh dunia tergolong dalam kategori “Tertekan” atau “Bermasalah” terkait dengan kesehatan mental mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya remaja dan orang muda, yang lebih sering melakukan self-diagnosis melalui informasi yang mereka temukan secara daring, termasuk di media sosial dan aplikasi kesehatan (WHO, 2022).
Di Indonesia, penelitian oleh Amalia (2024) pada 437 mahasiswa yang mayoritas perempuan usia 21-29 tahun menunjukkan 69,1% pernah self-diagnosis tanpa konsultasi ahli. Tingkat self-diagnosis sedang mendominasi (70%), dengan literasi kesehatan mental berkontribusi 12,7% terhadap perilaku ini. Artinya, semakin banyak informasi yang dikonsumsi, justru semakin tinggi kecenderungan untuk mendiagnosis diri sendiri secara keliru.
Ketika Self-Diagnosis Dibagikan sebagai Konten
Banyaknya akun media sosial seperti Tik Tok, Instagram, maupun Twitter yang sering kali membagikan konten mengenai kecemasan atau gangguan kesehatan mental dari influencer dan content creator memperparah kondisi ini. Kenyataannya mereka bukanlah seorang yang profesional dalam bidang psikologi. Namun karena konten yang dikemas menarik, membuat penonton percaya informasi tersebut valid.
Seperti halnya seorang influencer membagikan konten pengalaman pribadinya mengenai gejala anxiety, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan profesional. Penonton yang merasa memiliki pengalaman serupa langsung menyimpulkan bahwa mereka juga mengalami gangguan yang sama. Akibatnya, banyak penonton menganggap diri mereka juga mengidap gangguan kesehatan mental hanya karena merasa relate dengan cerita yang dibagikan.
Terlebih lagi, adanya validasi sosial dari komentar pengguna lain juga memperparah kondisi ini. Tak hanya itu fitur algoritma pada TikTok juga menjadikan seseorang semakin gempar melakukan self-diagnosis. Algoritma akan semakin sering menampilkan konten serupa berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Akibatnya, seseorang akan semakin sering terpapar konten kesehatan mental baik yang dibuat oleh profesional maupun sekadar influencer yang membagikan pengalaman tanpa latar belakang keilmuan yang memadai.
Langkah Bijak Memahami Gejala Mental
Lalu, bagaimana seharusnya kita memahami kondisi mental kita sendiri? Ada beberapa pendekatan ilmiah yang lebih aman dan bertanggung jawab.
1. Catat gejala (Journaling)
Mencatat gejala lewat journaling terbukti bermanfaat. Penelitian oleh Smith et al. (2018) menunjukkan bahwa kebiasaan mencatat yang dilakukan selama 12 minggu dapat mengurangi tekanan mental serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan psikologis. Hal ini mendukung langkah dalam mencatat gejala secara ilmiah untuk langkah awal self-diagnosis yang tepat.
2. Kenali pemicu stres
Studi Riachi et al. (2022) menjelaskan bahwa pemicu stress dapat berupa berbagai macam faktor seperti trauma interpersonal serta lingkungan yang saling berhubungan dan bervariasi antarindividu. Memahami pemicu pribadi membantu kita menganalisis kondisi mental dengan lebih objektif, bukan sekadar merasa relate dengan konten viral.
3. Konsultasi ke psikolog atau psikiater
Tidak ada yang bisa menggantikan diagnosa profesional. Konsultasi kepada psikolog atau psikiater secara segnifikan efektif dalam mendiagnosis serta memperbaiki kondisi mental pasien. Hal ini menegaskan akan pentingnya konsultasi pada pihak yang lebih profesional apabila mengalami gejala yang menjurus pada gangguan kesehatan mental.
Mengenali diri memanglah penting akan tetapi memahami diri dengan benar merupakan langkah yang jauh lebih penting. Bukan dengan label yang kita ciptakan sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang lebih terarah, berpedoman pada sains, dan dilandasi kejujuran diri terhadap diri sendiri.
Seseorang yang melakukan self-diagnosis bukanlah seseorang yang keliru sepenuhnya, hanya saja mereka perlu bimbingan untuk memahami diri dengan lebih tepat dan mendalam. Kesadaran akan kesehatan mental bukanlah sekadar cap yang harus dipakai dan di dipamerkan, melainkan sebuah proses panjang yang harus dirawat dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Hanya dengan pendekatan yang tepat, kesadaran diri dapat menjadi langkah awal menuju kesejahteraan mental yang sesungguhnya.
Penulis: Aliifah Rahmah*
*)Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta